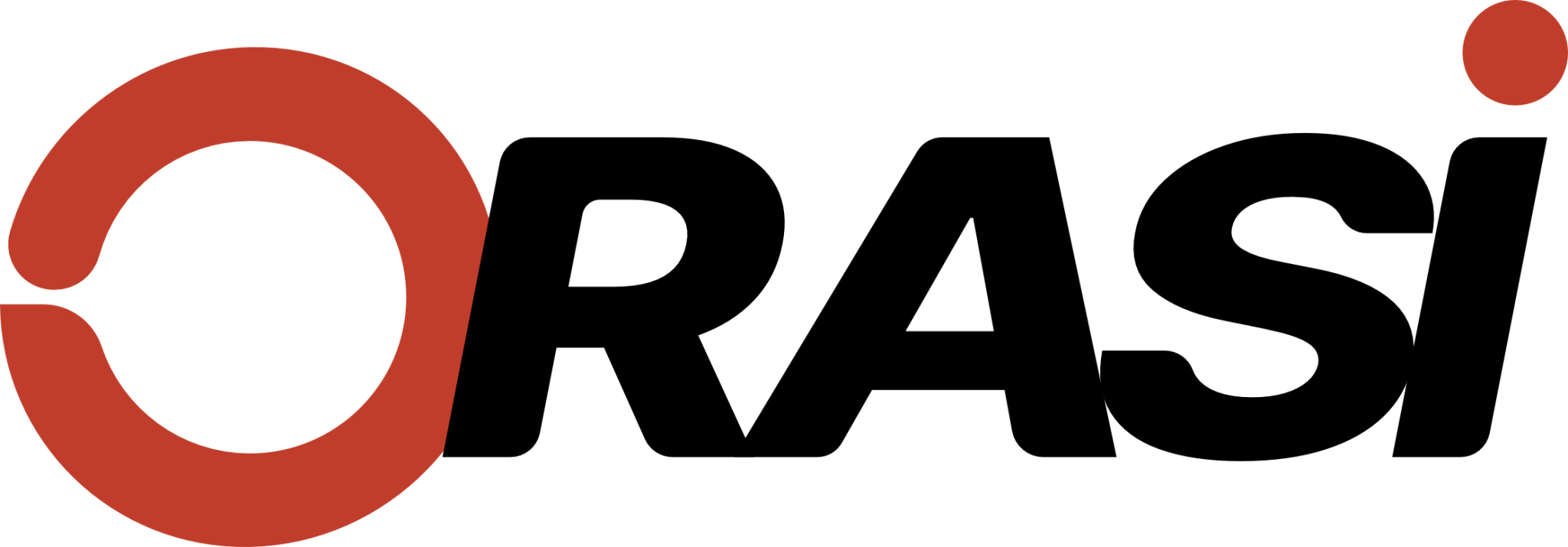Selamat datang di Bali, pulau di mana para dewa-dewi mungkin masih bersemayam, tapi dewa yang paling dipuja oleh anak muda saat ini tampaknya adalah Dewa Wi-Fi Kencang dan Dewi Colokan Listrik. Telah terjadi sebuah pergeseran lempeng tektonik sosial yang lebih dahsyat dari letusan Gunung Agung: evolusi budaya nongkrong anak muda Bali.
Dulu, sebuah lingkaran, satu sloki arak yang berputar, dan cerita ngalor-ngidul sampai pagi adalah puncak peradaban sosial. Kini? Puncak peradaban adalah menemukan kafe dengan password Wi-Fi yang tidak ribet dan barista yang bisa membuat latte art bentuk angsa, bukan bebek penyet.
Mari kita selidiki fenomena ini dengan keseriusan seorang turis yang menawar harga gelang di Sukawati.
Dari Lingkaran Arak ke Lingkaran Kecemasan Daring
Coba kita lakukan visualisasi.
Scene A: Nongkrong Era Baheula (sekitar 5-10 tahun lalu)
- Lokasi: Bale banjar, teras rumah, atau warung remang-remang yang sah secara adat.
- Perlengkapan: Satu botol arak, satu sloki yang higienitasnya dipertanyakan tapi mempererat persaudaraan, gitar butut, dan paru-paru baja untuk tertawa.
- Koneksi: Antarmanusia. Topik obrolan bervariasi dari filsafat hidup, nasib percintaan, hingga teori konspirasi lokal.
- Tujuan Akhir: Kebersamaan, mabuk, atau keduanya.
Scene B: Budaya Nongkrong Anak Muda Bali Era Kini
- Lokasi: Kafe aesthetic dengan dinding beton ekspos dan tanaman merambat palsu.
- Perlengkapan: MacBook, iPhone, noise-cancelling headphones, dan uang 50 ribu untuk secangkir kopi yang isinya lebih banyak busa susu.
- Koneksi: Indihome atau Biznet. Topik obrolan terjadi di kolom komentar Instagram, bukan di meja yang sama.
- Tujuan Akhir: Konten, menyelesaikan satu baris di Google Sheets, atau sekadar terlihat produktif.
Perubahannya drastis. Dulu kita berbagi cerita, sekarang kita berbagi hotspot. Ironis.

Kenapa Kopi?
Jadi, kenapa terjadi pengkhianatan besar terhadap arak ini? Apakah kopi lebih nikmat? Tentu tidak. Arak bisa membuatmu melupakan cicilan motor, kopi hanya membuatmu makin cemas soal deadline. Jawabannya lebih kompleks dan, tentu saja, lebih dangkal.
1. Kebutuhan Konten di Atas Segalanya
Mari jujur. Kamu tidak pergi ke kafe untuk kopinya. Kamu pergi ke sana sebagai sutradara, produser, dan bintang utama dari film berjudul “Kehidupanku Keren Sekali”. Secangkir kopi dengan busa berbentuk hati itu bukan minuman, itu properti syuting.
Sebelum diminum, kopi harus melalui serangkaian ritual sakral: difoto dari atas, dari samping, dijadikan latar Boomerang, diunggah ke Story dengan filter estetik dan lagu indie. Setelah didokumentasikan dengan layak bagi para pengikutmu, barulah kopi itu boleh mendingin dan kehilangan rasanya. Arak? Mana bisa difoto cantik? Paling-paling jadi Story buram dengan caption “MANTAPPPP” sebelum HP-mu jatuh.
2. Produktif (atau Pura-Pura Produktif)
Ada mitos urban legendaris di kalangan anak muda bahwa Wi-Fi kafe mengandung zat adiktif yang bisa meningkatkan produktivitas. Nongkrong sambil buka laptop memberi ilusi bahwa kita adalah seorang profesional muda yang sedang mengejar mimpi, padahal yang kita lakukan selama tiga jam hanyalah membalas satu email dan scrolling TikTok.
Ini adalah bentuk seni pertunjukan. Kita membayar puluhan ribu rupiah untuk “menyewa” atmosfer produktif. Minum arak, di sisi lain, terlalu jujur. Tujuannya jelas: relaksasi. Tidak ada kepura-puraan. Dan di dunia yang penuh kepura-puraan ini, kejujuran arak menjadi kurang menarik.
Arak Nggak Hilang, Cuma Pindah Kasta
“Jadi, apakah tradisi luhur minum arak ini akan punah ditelan zaman?” tanya seorang paman di desa dengan cemas.
Tenang, Paman. Arak tidak punah. Ia hanya melakukan rebranding dan naik kelas sosial.
Arak kini tidak lagi hanya di warung-warung. Ia sudah menyusup ke bar-bar mewah di Seminyak, menyamar dalam bentuk craft cocktail seharga 150 ribu dengan nama-nama keren seperti “Balinese Kiss” atau “Arak-mageddon Sunrise”. Ia kini diminum oleh turis dan kaum elit urban yang ingin merasakan “pengalaman lokal yang otentik” dengan harga yang tidak otentik sama sekali.
Jadi, arak hanya pindah dari ranah komunal ke ranah komersial. Sebuah takdir kapitalisme yang indah, bukan?
Tradisi Sesungguhnya Adalah Nongkrong Itu Sendiri
Pada akhirnya, pergeseran dari arak ke kopi bukanlah soal minumannya. Ini adalah tentang mediumnya. Tradisi Bali yang sesungguhnya bukanlah minum arak, melainkan berkumpul dan bersosialisasi. Entah itu dilakukan di atas tikar dengan sloki arak atau di atas kursi kayu minimalis dengan secangkir oat milk latte, esensinya tetap sama: mencari koneksi.
Hanya saja, koneksi yang dicari sekarang seringkali butuh password.
Jadi, lain kali kamu melihat sekelompok anak muda Bali di kafe yang saling diam sambil menatap layar masing-masing, jangan hakimi mereka. Mereka sedang menjalankan tradisi nongkrong versi terbaru. Mungkin 10 tahun lagi, kafe akan punah dan mereka akan nongkrong di dunia metaverse sambil minum kopi digital. Siapa tahu?
Yang jelas, selama ada hasrat untuk berkumpul dan menunda pekerjaan, budaya nongkrong anak muda Bali akan terus hidup dan berevolusi. Apapun minumannya.