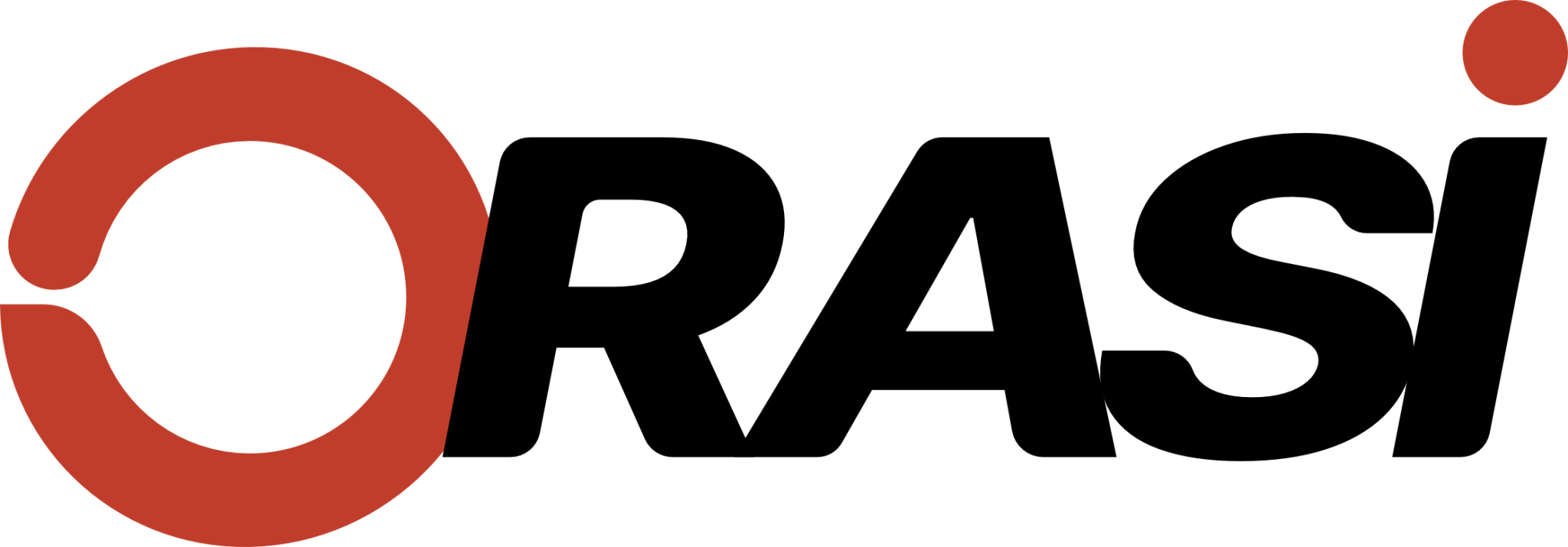Lagi asyik doomscrolling di malam hari, niatnya cuma mau lihat drama selebgram atau tren aneh di TikTok. Tiba-tiba, algoritma melempar sebuah granat digital ke timeline kamu: berita dari Detik Bali soal pembunuhan sadis di Kintamani.
Kita nggak lagi ngomongin perkelahian di bar. Judulnya aja udah bikin darah beku: dua nyawa melayang, satu sekarat. Kata kunci yang dipakai media, “sadis”, adalah kode bahwa ini bukan soal uang atau maling biasa. Ini soal parang yang bicara, soal dendam yang mungkin udah mendarah daging, soal pesan yang ingin disampaikan lewat darah.
Kalau kamu gali lebih dalam dari berita-berita semacam ini, polanya seringkali mirip. Gosipnya—entah benar atau tidak—sering berputar di tiga hal: tanah warisan, harga diri, atau utang piutang. Sengketa sepetak lahan yang nilainya sekarang meroket karena pariwisata. Sebuah ucapan yang dianggap menghina kehormatan keluarga. Sebuah janji yang diingkari.
Pelakunya, di mata hukum, adalah kriminal. Tapi coba kita pakai kacamata yang lebih gelap. Dalam kepalanya, mungkin dia bukan sekadar pembunuh. Mungkin, dia adalah seorang ‘jagoan’. Seorang ‘petarung’ yang lagi menegakkan keadilan versi dirinya sendiri, karena hukum adat dan hukum negara dirasa nggak cukup memuaskan egonya. Dia menyelesaikan masalah dengan cara paling purba: eliminasi.
Ini bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami akar rumput yang beracun. Dan akar ini, ironisnya, tumbuh dari tanah yang sama yang menumbuhkan mental petarung Desa Songan.
DNA Petarung: Dari Pahlawan Jadi… Musibah?
Sekarang, mari kita bedah konsep “petarung” ini.
DNA petarung orang Songan dan masyarakat Bali Aga di Kintamani itu ditempa oleh musuh yang jelas: Gunung Batur. Musuh mereka adalah alam yang ganas, tanah yang labil, dan ancaman kelaparan. Bertarung melawan alam butuh kerja sama. Solidaritas. Kamu nggak bisa egois kalau mau selamat dari letusan gunung. Mental petarung ini lahir untuk melindungi komunitas. Sifat keras mereka adalah tameng untuk bertahan hidup bersama.
Sekarang, fast forward ke tahun 2025.
Gunung Batur relatif tenang. Musuh purba itu lagi tidur. Tapi DNA petarung itu nggak hilang, dia cuma bingung cari lawan. Tekanan hidup modern—harga tanah yang gila-gilaan, persaingan ekonomi, gengsi sosial—menciptakan musuh-musuh baru yang nggak kelihatan. Musuhnya sekarang adalah tetangga sendiri.
DNA yang dulu jadi tameng komunitas, sekarang jadi senjata makan tuan. Sifat keras yang dulu untuk menghadapi alam, sekarang dipakai untuk menghadapi sesama. Harga diri disentil dikit, sikat. Tanah diserobot sejengkal, bacok. Konsep “jagoan” yang dulu mungkin adalah pahlawan desa, kini berpotensi jadi preman lokal yang menyelesaikan sengketa di ujung parang.
Berita pembunuhan sadis itu adalah manifestasi paling gelap dari evolusi DNA petarung ini. Ketika semangat juang kehilangan musuh mulianya, ia akan menciptakan monster di pekarangan rumah sendiri.
Songan: Arsip Hidup Mentalitas Dua Sisi
Di sinilah Desa Songan jadi relevan banget. Mereka adalah arsip hidup, ground zero dari mentalitas ini yang sudah eksis sejak 994 M, menjadi saksi bisu ribuan tahun pertarungan.
Mereka adalah bukti nyata sisi positif DNA ini:
- Ketangguhan: Mampu bertahan ribuan tahun di lokasi yang rawan bencana.
- Kemandirian: Punya aturan dan tradisi sendiri yang mereka jaga mati-matian.
- Harga Diri: Kebanggaan sebagai Bali Aga, sebagai klan Pasek Kayu Selem.
Tapi, seperti koin, selalu ada sisi sebaliknya. Di balik kebanggaan itu, ada potensi bahaya dari sifat yang sama: keras kepala, sulit menerima kompromi, dan meledak jika kehormatan diinjak-injak.
Jadi, Pelajarannya Apa Buat Kita?
Saat kamu datang ke Kintamani, dan khususnya ke desa kuno seperti Songan, kamu nggak lagi datang sebagai turis biasa. Kamu datang sebagai saksi dari sebuah paradoks budaya. Di sini kamu nggak akan cuma lihat pemandangan danau yang katanya bisa “menyembuhkan”, tapi akan lihat jejak-jejak mentalitas yang bisa membangun sebuah peradaban… sekaligus menghancurkannya dalam semalam.
Ini bukan lagi soal reality check untuk masalah hidup kamu yang sepele. Ini soal memahami bahwa “karakter kuat” dan “potensi kekerasan brutal” seringkali hanya dipisahkan oleh sehelai benang tipis bernama tekanan.
Kesimpulannya?
Berita pembunuhan di Kintamani itu bukan anomali. Itu adalah gejala. Gejala dari sebuah spirit purba yang sedang berjuang—dan kadang gagal—untuk beradaptasi dengan dunia modern.
Songan udah jadi petarung sejak 1000 tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, di zaman ini, siapa lawan mereka sebenarnya? Gunung berapi, atau… diri mereka sendiri?