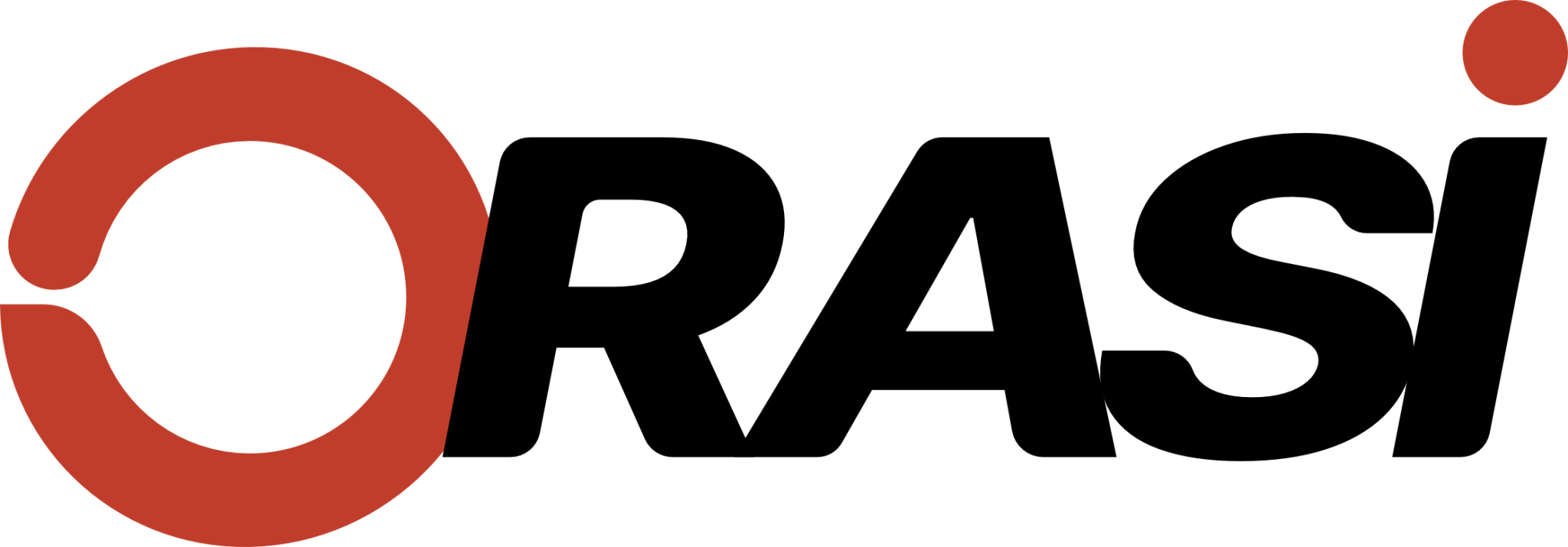Kemarin berita isinya Tesso Nilo dibabat habis, terus Sumatera langsung banjir bandang nggak karuan. Kita di Bali? Paling scroll doang sambil nyeruput iced latte, terus batin, “Ah, itu urusan orang sana, jauh. Bali aman, ada sesajen tiap hari.”
Stop playing victim, Kle! Jarak boleh beda pulau, tapi penyakitnya sama: Lupa Diri dan Mentalitas Serakah. Kita nggak bisa lagi pura-pura buta kalau bencana alam di sana itu cermin buat kita di sini. Bedanya, kalau di Sumatera bencananya adalah banjir bandang yang meratakan desa, bencana kita di Bali itu namanya Macet Parah dan Subak yang Terlupakan.
Paru-Paru Sumatera Dibabat, Jantung Bali Dibeton
Coba deh kita jujur. Apa sih benang merah antara hutan yang dibabat di Tesso Nilo (buat kebun sawit atau lahan) sama fenomena di Bali? Gengsi Pembangunan.
Di sana, pohon-pohon besar yang jadi resapan dan paru-paru alam dihabisi. Kalau Paru-Paru hilang, jelaslah alam batuk-batuk, terus muntah air (banjir). Nah, kalau di Bali, kita nggak babat hutan, tapi kita babat Jantungnya. Jantung itu namanya Subak—sistem irigasi sawah tradisional yang cerdas, yang harusnya jadi pengontrol air alami.
Kita rela ganti hamparan sawah hijau yang jadi resapan air, jadi Beach Club, Villa Sultan, atau Creative Hub (yang isinya cuma beton panas).
Ada yang bilang, “Ini untuk pariwisata, melestarikan budaya.” Tapi kok melestarikannya malah dengan semen yang nutupin semua resapan air? Itu bukan ngayah buat melestarikan budaya, itu namanya ngorbanin (mengorbankan) masa depan cuma buat keuntungan sesaat.
Tri Hita Karana Versi Baru: Tri Hita Kredit
Kita semua hafal di luar kepala filosofi Tri Hita Karana: Hubungan harmonis dengan Tuhan (Parahyangan), Sesama (Pawongan), dan Alam (Palemahan). Ini bukan cuma buat mantra di Pura, nak. Ini buat lifestyle!
Tapi coba lihat kenyataan:
- Parahyangan: Rajin mebanten (berdoa) dan metirtha (ambil air suci). Tapi habis sembahyang, tanah di sebelah Pura kita jual buat ruko.
- Pawongan: Ngomongin solidaritas di sosmed, tapi saling sikut harga properti biar untung gede, meskipun tetangga jadi korban macet akibat pembangunan kita.
- Palemahan: Sawah di depan rumah kita sendiri kita rela jual buat minimarket turis. Penjor Galungan boleh tinggi, gengsi kita jangan sampai mengorbankan fondasi tanah.
Kalau di Sumatera, mereka melawan banjir. Kalau di Bali, kita melawan Macet yang nggak masuk akal, Kekeringan yang makin parah tiap musim panas, trus sekarang hujan dikit udah banjir di Denpasar dan sekitarnya. Kle, itu semua efek domino dari hilangnya resapan air karena kita terlalu bangga sama beton dan kaca.
Sistem alam nggak peduli seberapa estetik feed IG-mu. Air itu butuh jalan, dan kalau jalannya ditutup, dia pasti cari jalan sendiri. Besok lusa, kalau musim hujan, air bakal parkir di depan rumahmu dan bilang, “Neh, amah!”
Subak: Dari Warisan Dunia Jadi Background Foto
Kita bangga banget Subak diakui UNESCO. Tapi coba, berapa banyak dari kita yang masih benar-benar peduli sama fungsi Subak?
Subak sekarang lebih sering jadi background kafe buat Gen Z foto OOTD atau tempat jogging turis, bukan lagi sistem pertanian yang sakral. Kita lebih bangga beach club di atas tebing yang berpotensi longsor daripada air yang mengalir lancar di Subak.
Intinya, bencana banjir di sana, macet parah dan kekeringan di sini, semua itu efek domino dari keserakahan yang sama. Stop playing victim dengan bilang, “Itu urusan orang luar yang bawa modal.” Kita punya kearifan lokal yang harusnya jadi benteng, tapi malah kita sendiri yang bongkar.
Jadi, cai mau pilih mana? Selamatkan gengsi dan terus-terusan mengeluh macet, atau mulai sadar dan selamatkan Palemahan?