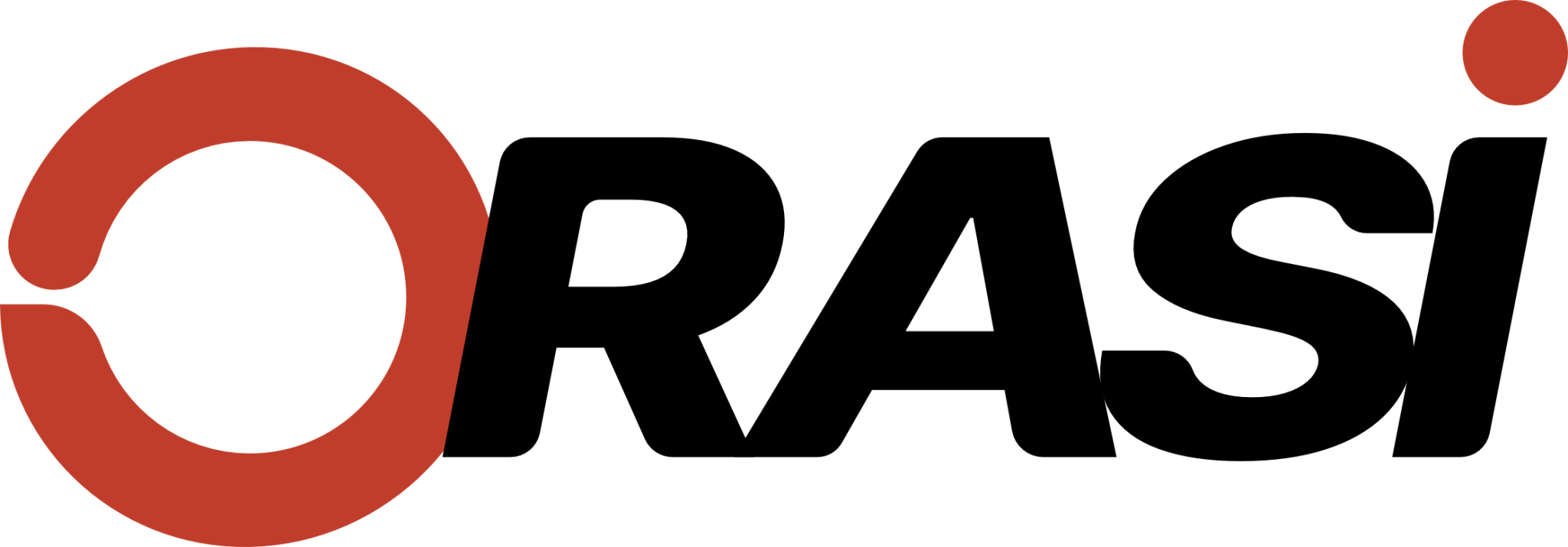Halo Netizen yang budiman! Sudah lelah hidup di dunia yang vibes-nya makin hari makin kayak sinetron? Selamat datang di episode terbaru: Fenomena ‘Kampung WNA’ dan Ancaman Gesekan Sosial-Budaya.
Kita semua tahu, pariwisata itu katanya lokomotif ekonomi. Tapi, kalau lokomotifnya malah nabrak rumah sendiri, apa iya masih patut disanjung?
Fenomena di beberapa tempat (khususnya Bali, ya, si “surga” yang makin padat) udah kayak setting film kolonial, tapi dengan plot twist yang lebih dark. Sekelompok WNA mulai membentuk komunitas yang super eksklusif, bahkan dijuluki “Kampung Rusia” atau “kampung negara tertentu” di Ubud, Canggu, dan sekitarnya. Mereka hidup private, tertutup, seolah-olah Indonesia ini adalah taman bermain pribadi mereka yang bebas dari aturan.
Cuma “Tamu”, Tapi Berlagak Tuan Rumah
- Melanggar Adat, No Big Deal: Mulai dari telanjang di tempat suci, yoga di atas pohon keramat, sampai joget ugal-ugalan di jalanan. Bagi mereka, sepertinya kearifan lokal itu hanyalah aesthetic untuk di-upload, bukan untuk dihormati. Ketika ditegur, reaksinya kadang lebih drama daripada influencer yang ketahuan endorse produk abal-abal.
- Rebut Rezeki Lokal: Survival of the Fittest Ala Bule: Ini yang paling bikin emosi. WNA datang pakai visa turis, tapi flexing buka usaha ilegal. Buka barber shop, biro perjalanan motor, spa, bahkan jualan sayur! Coba, tukang cukur lokal, guide lokal, dan UMKM kita suruh bersaing sama mereka yang modalnya dollar? Ini bukan persaingan sehat, ini namanya pemaksaan diet ketat untuk perut orang lokal. Mereka merebut peluang yang seharusnya jadi privilege warga negara sendiri.
- Ugal-ugalan di Jalan: Kamu naik motor butut, kena tilang karena lampu mati. Mereka? Naik motor gede tanpa helm, selfie di tengah jalan, bahkan tabrakan dan ngamuk ke polisi. Hukuman? Paling banter viral sebentar, lalu deportasi… yang biayanya (mungkin) udah masuk budget liburan mereka.
Siapa yang Paling Diuntungkan dari Overtourism?
Jawabannya sudah jelas: Bukan kamu, bukan juga UMKM lokal.
Pariwisata massal, dengan segala drama dan kekacauan yang dibawanya (macet, sampah numpuk, krisis air), ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir investor besar, pemilik modal asing, dan pejabat yang pura-pura nggak tahu.
Kita dapatnya apa? Gesekan sosial. Warga lokal jadi kzl setengah mati karena harus menahan diri melihat tingkah laku WNA yang sok raja. Budaya kita perlahan tergerus karena dipaksa jadi “dekorasi” agar feed Instagram turis tetap on point.
Coba pikirkan: Devisa yang masuk itu sebanding nggak sih dengan harga diri, lingkungan, dan ketenangan hidup yang harus kita korbankan? Apakah kita harus menerima kenyataan bahwa di negara sendiri, kita cuma jadi pelayan untuk “Sultan Global” ini?
Solusi? No Mercy Imigrasi
Sudah saatnya kita berhenti pakai filosofi “tamu adalah raja” kalau tamunya ngajak ribut.
- Satgas Imigrasi Level Up: Jangan cuma rajin kalau sudah viral. Operasi pengawasan harus rutin, random, dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai WNA ilegal yang buka usaha lebih nyaman daripada WNI yang bayar pajak.
- Hukum Seberat-beratnya: Yang melanggar hukum, apalagi yang merebut lapangan kerja lokal, harus ditindak tegas. Deportasi itu bukan liburan gratis tahap kedua. Wajibkan mereka bayar denda yang bikin mereka kapok sebelum diusir.
- Filtrasi Ketat di Awal: Pemerintah harusnya gentle untuk membatasi atau menyeleksi siapa yang boleh masuk. Kita butuh turis berkualitas yang menghargai adat dan mau menghabiskan uang, bukan yang datang untuk numpang hidup dan ngerusak.
Intinya, kalau kita nggak tegas, fenomena ‘Kampung WNA’ ini akan terus berkembang, dan kita, sebagai tuan rumah, pada akhirnya cuma akan jadi penjaga pintu di rumah kita sendiri. Selamat datang di masa depan yang suram.