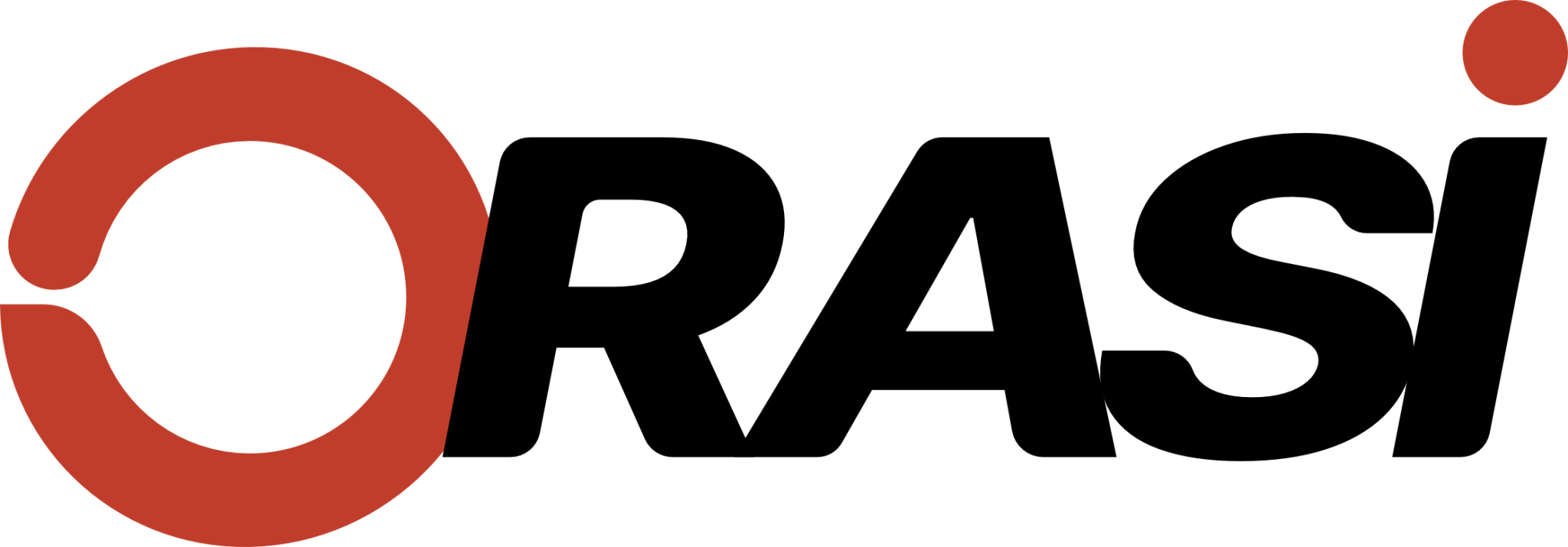Sebuah polemik hangat tengah menjadi perbincangan di Pulau Dewata. Kontroversi donasi guru Bali untuk korban banjir ini memicu dilema unik, layaknya sebuah hubungan asmara yang rumit. Di satu sisi, ada niat tulus untuk bergotong royong. Namun di sisi lain, ada “surat cinta”—sebuah imbauan tak tertulis yang terasa seperti kewajiban—yang membuat suasana menjadi canggung.
Niat awalnya tentu sangat baik, yaitu mengajak para guru dan ASN untuk menunjukkan solidaritas kepada sesama yang tertimpa musibah. Sayangnya, ajakan ini datang dengan rincian nominal yang sudah ditentukan. Sumbangan dengan patokan mulai dari Rp100.000 hingga Rp1,25 juta berdasarkan jabatan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Akibatnya, hubungan yang seharusnya dilandasi empati tulus ini terasa seperti sebuah transaksi yang canggung.
Niat Baik di Balik Narasi Gotong Royong
Menanggapi kehebohan publik, Pemerintah Provinsi Bali segera memberikan klarifikasi. Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa ini semua murni soal semangat gotong royong khas Bali. Menurutnya, inisiatif ini sepenuhnya sukarela. “Kalau mau ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa,” ujar Koster.
Pemerintah menjelaskan bahwa acuan nominal dibuat hanya untuk mempermudah, bukan untuk memaksa. Mereka meyakinkan bahwa kepedulian ini tulus dan tidak memerlukan surat keputusan (SK) formal. Ini adalah narasi yang indah tentang solidaritas. Namun, praktik di lapangan dirasakan berbeda oleh banyak pegawai.
Dilema ‘Surat Cinta’ dengan Daftar Harga
Meskipun tidak ada surat edaran resmi, instruksi lisan ini terasa lebih mengikat. Instruksi tersebut dikoordinir melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan menyebar hingga ke dinas lain. Hal ini menciptakan dilema besar bagi para pegawai.
Jika menolak, mereka khawatir dianggap tidak solidaris. Namun jika menerima, terasa memberatkan bagi sebagian orang. Inilah inti dari kontroversi donasi guru Bali tersebut: ajakan sukarela yang hadir dengan daftar harga dan pengawasan sosial. Solidaritas yang tulus pun berisiko berubah menjadi administrasi kewajiban.
Bukan ‘Surat Cinta’ Pertama: Imbauan Serupa untuk ASN Bali
Tentu saja, para pegawai di Bali sudah tidak asing dengan berbagai jenis “surat cinta” ini. Donasi banjir hanyalah episode terbaru dari serial panjang yang sudah sering terjadi. Berikut adalah beberapa edisi klasik lainnya yang kerap diterima ASN di Bali.
1. Edisi Cinta Produk Lokal (Gerakan Bela Beli)
Ini adalah episode yang paling sering tayang. Dengan dalih membangkitkan ekonomi, muncul imbauan (yang terasa wajib) untuk membeli produk lokal seperti arak Bali atau beras petani. Misi mulia ini dimulai dari sedikit ‘memaksa’ dompet para abdi negara. Sebuah skema subsidi silang yang sungguh romantis, bukan?
2. Edisi Seragam dan Penampilan (Budaya Itu Mahal, Gung!)
Pegawai adalah etalase budaya Bali. Karena itu, ada kewajiban tak tertulis untuk selalu update koleksi busana adat, terutama saat ada motif endek baru yang diluncurkan untuk acara provinsi. Gaji UMR, tapi tuntutan penampilan harus selevel influencer budaya. Dompet menangis di balik senyum tresna Bali.
3. Edisi Partisipasi Sukseskan Acara
Untuk memastikan acara pemerintah terlihat sukses, pegawai menjadi audiens utama. Mereka “diwajibkan” ikut gerak jalan atau membeli tiket konser amal yang diadakan pemerintah. Teori relativitas terbukti di sini: partisipasi itu relatif, antara sukarela dan surat tugas.
4. Edisi Iuran Abadi
Di luar potongan resmi, selalu ada iuran “gotong royong” lainnya. Misalnya, pengumpulan Dana Punia untuk upacara besar di Pura Besakih. Nominalnya mungkin “seikhlasnya,” tapi daftar nama penyumbang seringkali dipajang. Sebuah konsep kerelaan yang terukur dan terdokumentasi.
Pada akhirnya, semangat gotong royong adalah jiwa Bali yang harus terus dirawat. Namun, ketika ia datang dalam format “surat cinta” dengan lampiran tagihan, romansa kebersamaan itu bisa memudar, menyisakan dilema di hati para abdi negara.