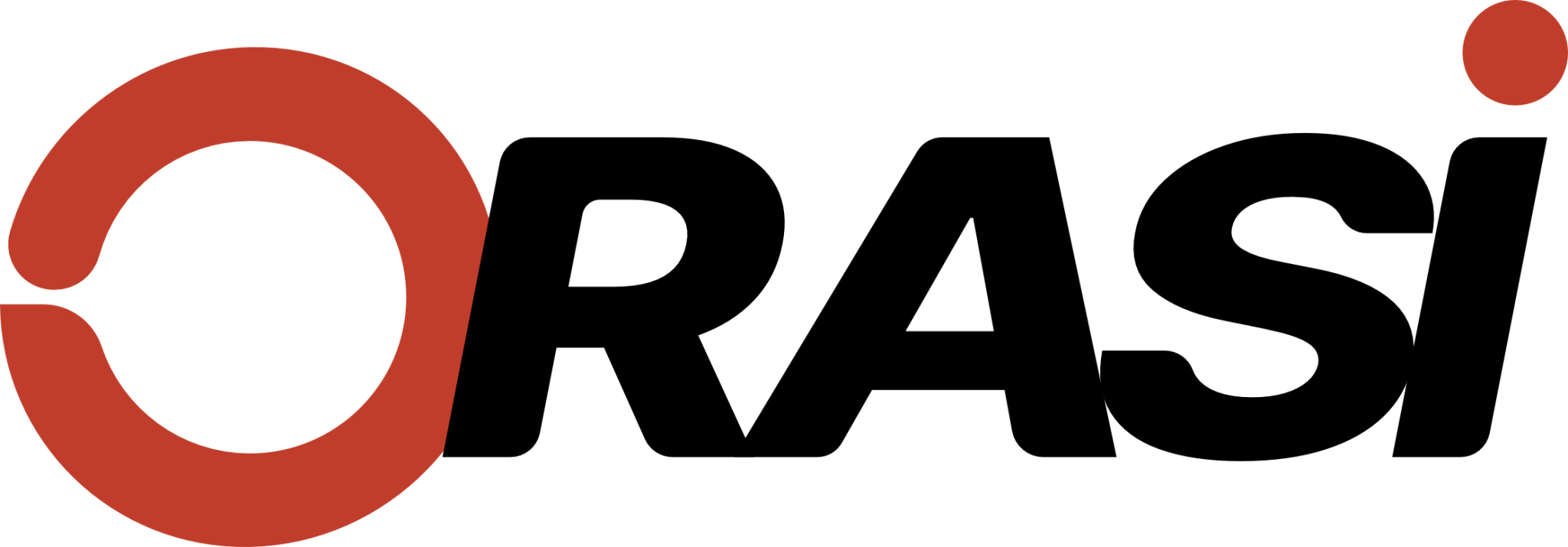Kabar gembira untuk kita semua! Bandara Ngurah Rai kembali padat merayap. Statistik kedatangan wisatawan melesat tinggi menembus langit—sama tingginya dengan tumpukan sampah di TPA Suwung yang baunya mulai bersaing dengan aroma dupa.
Secara visual, Bali terlihat “pulih”. Jalanan macet total, shortcut Canggu sudah resmi menjadi arena simulasi film Mad Max dengan kearifan lokal, dan antrean di tempat hits mengular sampai memakan bahu jalan. Di atas kertas, Bali sedang pesta pora. Pejabat tersenyum lebar baca laporan BPS. Tapi kalau kita cek saldo rekening warga lokal dan kas pendapatan daerah? Hening. Sepi. Bunyi jangkrik lagi konser.
Ternyata, kedatangan jutaan manusia ini menghadirkan mukjizat ekonomi baru: Wisatawannya membludak, tapi duitnya entah menguap ke dimensi lain. Berikut adalah analisis (kurang) ilmiah kenapa Bali perlahan berubah dari destinasi wisata premium menjadi panti sosial internasional.
1. Ekonomi “Lingkaran Setan” (Sirkel Bule untuk Bule)
Selamat datang di “Republik Canggu” dan sekitarnya. Bule datang ke Bali, sewa vila punya Bule (yang di atas kertas namanya Pak Wayan, tapi sertifikat aslinya dipegang Mister John di brankas), sewa Nmax di rental ilegal punya Bule, belajar Ecstatic Dance sama instruktur Bule, ditato sama Bule, lalu makan sourdough di kafe milik Bule.
Orang lokalnya di mana? Oh, tenang, kita tetap ada peran krusial. Kita yang kebagian tugas mulia: nyapu halaman vila mereka, ngangkut sampah sisa pesta mereka, dan jadi penonton VIP di pinggir jalan melihat mereka “living their best life”. Uangnya berputar kencang bak gangsing, tapi cuma di sirkel mereka sendiri. Kita cuma jadi NPC (Non-Playable Character) di tanah kelahiran sendiri, yang fungsinya cuma senyum dan bilang “Yes, Sir”.
2. Gaya Sultan, Dompet UMR (Pasukan Nasi Jinggo)
Dulu kita menyambut “Dollar Walking”. Sekarang? Kita kedatangan pasukan “Healing Low Budget” dan “Digital Nomad” paket hemat. Ini adalah spesies wisatawan yang duduk di kafe coworking space selama 8 jam, numpang charge laptop, numpang Zoom meeting, pakai Wi-Fi sepuasnya, tapi cuma pesan satu cangkir Long Black (tanpa gula, biar irit).
Mereka juga tipe yang nawar harga suvenir di Pasar Seni Sukawati lebih sadis daripada ibu-ibu komplek nawar sayur. Mereka makan nasi jinggo bukan karena ingin mencicipi kuliner lokal, tapi karena itu satu-satunya cara bertahan hidup biar sisa uangnya bisa buat beli bir di minimarket (bukan di bar, mahal). Mereka datang bukan membawa devisa, tapi membawa beban infrastruktur. Tapi ya sudahlah, yang penting feed Instagram mereka estetik, kan? Biar kelihatan sukses “Work From Paradise”.
3. Investasi Jalur “Nominee” & Seminar “Financial Freedom”
Banyak yang bilang Bali banjir investasi. Benar, tapi investasinya seliar pengendara Nmax bertelanjang dada yang nggak tahu fungsi lampu sein. Transaksi properti dan jasa kini canggih: via dompet digital luar negeri atau Kripto. Pajak Hotel dan Restoran (PHR)? Apa itu? We don’t do that here.
Sementara Dinas Pajak pusing mengejar target, para expat ini sibuk bikin seminar “How to Make 6 Figures While Living in Bali” atau “Manifesting Abundance”. Mereka mengajarkan cara kaya raya, padahal tinggal di sini pun karena lari dari pajak tinggi di negaranya sendiri. Ironi yang sangat membagongkan.
4. Barter Tak Seimbang: Kita Dapat Macet, Mereka Dapat Sunset
Ini adalah pertukaran paling adil abad ini. Mereka mendapatkan surga tropis, budaya eksotis, dan kesabaran warga lokal yang tak terbatas. Sebagai gantinya, kita mendapatkan:
- Kemacetan abadi yang bikin tua di jalan (Denpasar-Canggu rasanya kayak Denpasar-Surabaya).
- Gentrifikasi brutal: Harga tanah makin gila, sampai warga lokal kalau mau beli rumah pilihannya cuma dua: pindah ke kabupaten sebelah atau nunggu warisan (itu pun kalau tanahnya belum dijual bapaknya buat beli Rubicon).
- Air tanah kering: Disedot ribuan sumur bor vila privat, sementara warga desa sebelah mulai krisis air bersih.
- Hiburan Gratis: Tontonan bule tantrum, bugil di pohon keramat, atau debat sama polisi soal helm.
Kesimpulan: Bali “Full House”, Tapi Kasirnya Kosong
Bali sekarang ibarat restoran yang kursinya penuh sesak, dapurnya ngebul, pelayannya lari-larian keringatan sampai pingsan, tapi saat dicek di kasir… yang bayar cuma segelintir. Sisanya “ngutang”, bayar pake exposure, atau bawa bekal sendiri dari rumah.
Mungkin sudah saatnya kita ganti slogan penyambutan di bandara. Bukan lagi “Om Swastiastu”, tapi “Om, Kalau Miskin Jangan Healing di Sini Dong, Om.”