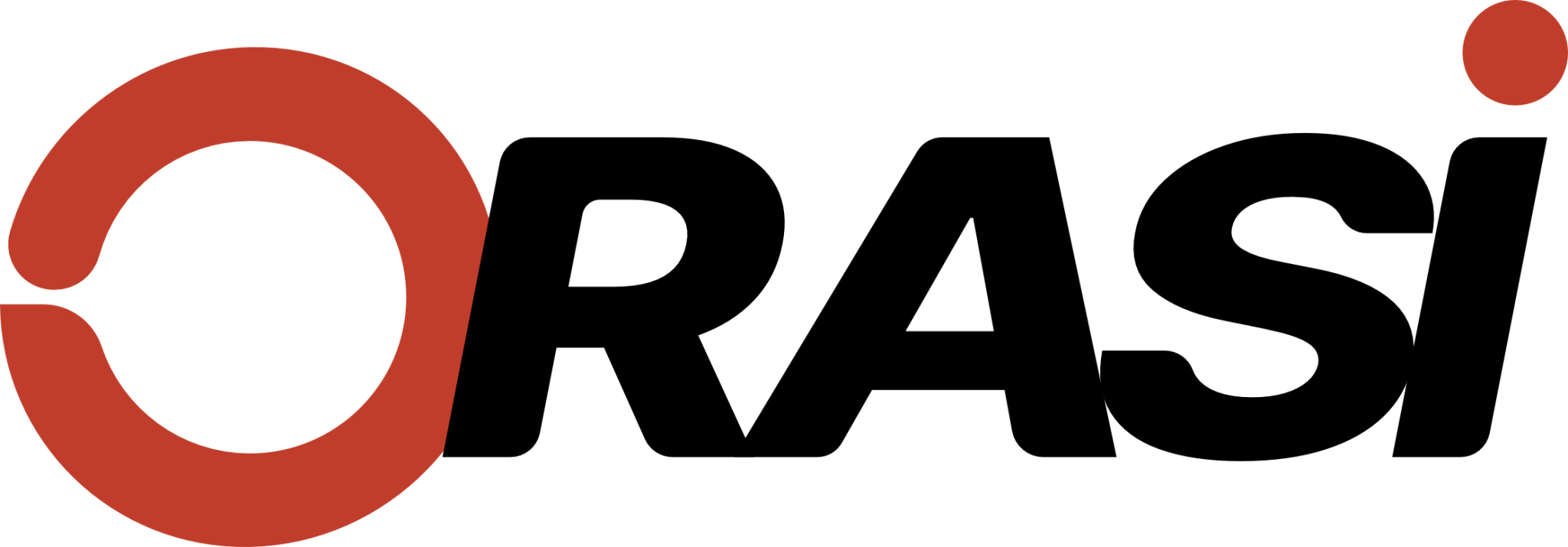Cesss… Suara minyak panas bertemu adonan telur pecah adalah salah satu simfoni paling jujur di setiap dapur Bali. Ini adalah suara kepastian. Suara bahwa hari ini, setidaknya untuk satu porsi makan, urusan perut aman. Dari simfoni sederhana inilah lahir sebuah jargon agung yang meresap ke sanubari Gen Z hingga kaum kolonial di Bali: “Taluh Goreng Ade Hasil.”
Awalnya, frasa ini adalah oase di tengah gurun ekspektasi. Sebuah perayaan atas hal-hal kecil, tamparan lembut bagi mereka yang mengejar kemewahan tapi lupa cara bersyukur. Ia adalah anti-tesis dari “hustle culture” yang melelahkan. Ia sederhana, ia nyata, ia membumi. Namun, seperti banyak hal di Bali, sesuatu yang indah seringkali menyembunyikan retakan di bawahnya. Riset asal-asalan ini mencoba mengintip retakan tersebut, bertanya: apakah mantra ini telah berevolusi menjadi senandung pengantar tidur bagi nalar kritis kita?
Penelitian ini tidak menggunakan survei kuantitatif atau wawancara mendalam. Data dikumpulkan dari pengamatan kemacetan, bisik-bisik di warung kopi saat hujan, dan scroll tanpa henti di kolom komentar media sosial. Validitasnya mungkin diragukan, tapi relevansinya terasa begitu dekat.
Studi Kasus #1: Banjir Setinggi Betis dan Logika Wajan Panas
Setiap kali hujan deras mengguyur Denpasar atau Kuta, skenario yang sama terulang: jalanan menjadi sungai cokelat, motor-motor mogok, dan air keruh mulai menjilat teras rumah. Ini bukan lagi anomali, ini adalah agenda rutin musim hujan. Ini adalah masalah kolektif yang disebabkan oleh pembangunan serampangan, drainase yang tersumbat oleh ketidakpedulian, dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.
Di tengah kepungan air, bagaimana “Filosofi Taluh Goreng Ade Hasil” bekerja?
Seseorang di dalam rumahnya yang nyaris terendam mungkin akan berpikir, “Astungkara di dalam masih kering, masih bisa nyalain kompor.” Sambil menggoreng telur, ia melihat berita tentang banjir di ponselnya. Responnya bukanlah kemarahan atau tuntutan pada pemerintah, melainkan kelegaan personal. “Yang penting saya dan keluarga aman, bisa makan. Urusan banjir itu rumit, biar diurus yang di atas.”
Di sini, “hasil” dari taluh goreng menjadi benteng pertahanan psikologis. Ia menciptakan sekat antara “masalahku” (perut lapar) dan “masalah kita” (banjir). Kelegaan sesaat karena sepiring nasi dan telur goreng menjadi lebih berharga daripada solusi jangka panjang untuk lingkungan tempat tinggalnya. Logika wajan panas telah mengalahkan logika ruang hidup bersama.
Studi Kasus #2: Riuh Demo Agustus dan Heningnya Partisipasi
Mari kita putar waktu ke Agustus kemarin. Ratusan, bahkan ribuan, anak muda dan aktivis turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan terhadap sebuah kebijakan (mari kita sebut saja kebijakan X) yang dianggap akan semakin merusak wajah Bali. Mereka berpanas-panasan, berteriak, membawa spanduk. Sebuah “hasil” yang mereka perjuangkan bersifat abstrak dan untuk masa depan: menjaga Bali.
Lalu, di mana para penganut “Filosofi Taluh Goreng Ade Hasil” saat itu?
Sebagian besar mungkin terjebak macet karena demo tersebut. Sumpah serapah keluar dari mulut mereka. “Gara-gara orang-orang ini, saya jadi telat pulang. Bikin ribet saja. Demo begitu apa ada hasilnya? Nggak jelas. Mending saya, jelas kerja dari pagi sampai sore, pulang, taluh goreng, ade hasil.”
Lihat polanya? Aksi kolektif yang hasilnya tidak pasti dan berisiko dianggap sebagai kesia-siaan. Sementara, rutinitas individual yang hasilnya pasti (gaji bulanan, makanan di atas meja) dianggap sebagai satu-satunya bentuk perjuangan yang logis. Perjuangan untuk Bali disederhanakan menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Keberanian untuk turun ke jalan dianggap tidak lebih berharga dari keberanian menyalakan kompor gas.
Antara Sepiring Nasi dan Nasib Pulau Dewata
“Taluh Goreng Ade Hasil” adalah cermin dua sisi. Di satu sisi, ia adalah kearifan lokal modern tentang pentingnya rasa cukup. Di sisi lain, ia adalah gejala dari masyarakat yang mungkin mulai lelah. Lelah dengan masalah yang tak kunjung usai, lelah dengan politik yang rumit, lelah dengan perubahan yang terlalu cepat.
Keletihan ini melahirkan mekanisme pertahanan: mengecilkan skala tanggung jawab. Tanggung jawab pada pulau, pada masyarakat, pada generasi mendatang, diciutkan menjadi hanya sebatas tanggung jawab pada perut sendiri dan keluarga inti.
Bahayanya adalah ketika “hasil” yang kita rayakan hanyalah sepiring telur goreng, sementara di luar sana, “aset” kita bersama—berupa lingkungan yang sehat, tata ruang yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat—sedang digoreng habis oleh kepentingan segelintir orang.
Pada akhirnya, kita semua butuh makan. Kita semua butuh “taluh goreng” agar bisa berpikir. Tapi pertanyaan renungannya adalah: jika kita hanya fokus menggoreng telur di dapur kita masing-masing, siapa yang akan memastikan bahwa rumah kita tidak akan tenggelam oleh banjir atau dijual kepada penawar tertinggi?
Jangan sampai kita begitu sibuk memastikan “ade hasil” di piring kita, hingga kita tidak sadar bahwa meja makannya sendiri sudah lapuk dan hampir rubuh.