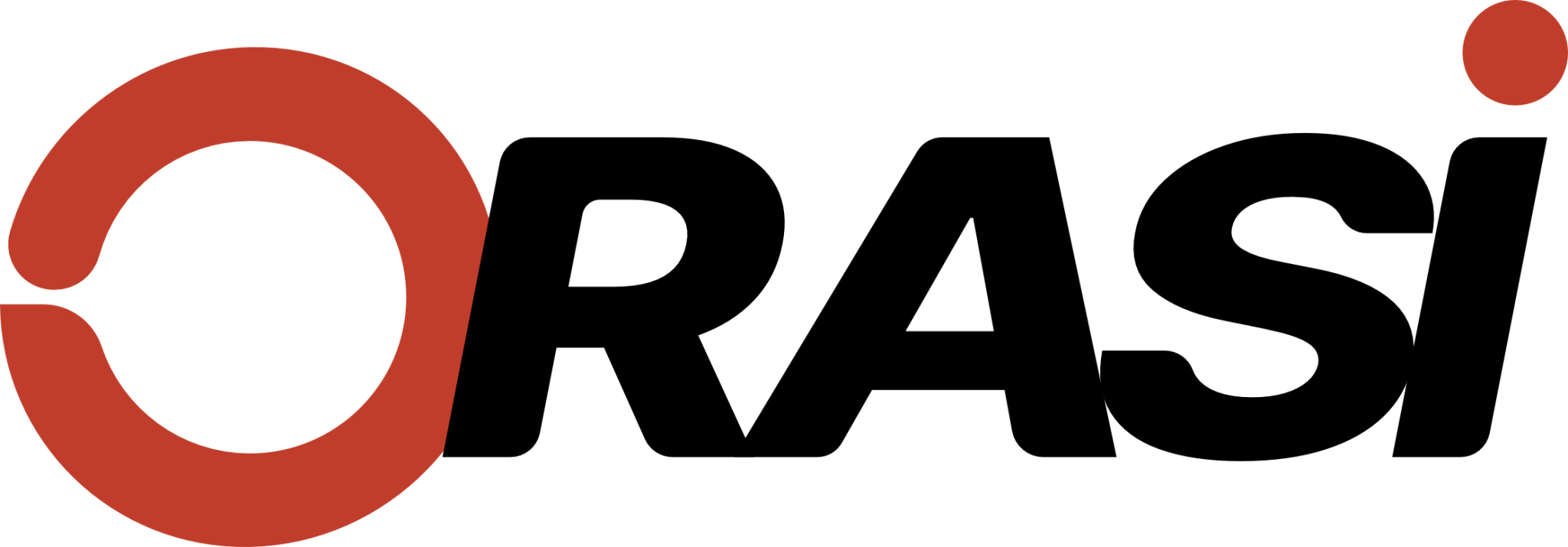Oke, mari kita jujur-jujuran. Tekanan hidup di Bali itu nyata, se-nyata tagihan pinjol di akhir bulan. Belakangan ini, isu tersebut meledak lagi gara-gara insiden tragis di Jembatan Tukad Bangkung, Plaga, yang sukses jadi trending topic.
Peristiwa kelam ini kayak alarm kebakaran yang nggak bisa di-snooze lagi. Ini bukan cuma berita duka, tapi juga sebuah memo brutal yang memaksa kita bertanya: Kenapa di pulau yang kita jual sebagai “surga dunia” ini, banyak banget yang merasa jiwanya lagi di neraka?
Mari kita bedah bersama, tanpa filter, tanpa basa-basi manis khas tour guide.
Bali Juara 1 ‘Lomba Lelah Hidup’? Kok Bisa?
Inget kan beberapa tahun lalu mantan Menkes kita, dr. Terawan, pernah nyeletuk kalau Bali itu provinsi dengan angka bunuh diri tertinggi se-Indonesia? Well, selamat buat kita! Kita juara satu untuk kategori yang nggak ada di brosur pariwisata manapun.
Ini adalah ironi level tertinggi. Orang dari seluruh penjuru bumi datang ke Bali buat healing, sementara sebagian dari kita yang tinggal di sini justru butuh di-healing paling serius. Kita ekspor kedamaian, tapi impor kecemasan. Logikanya di mana, coba? Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan hidup di Bali bukanlah mitos belaka.
3 Biang Kerok Utama Pemicu Tekanan Hidup di Bali (Yang Nggak Ada di Brosur Turis)
Jadi, siapa saja tersangka utamanya? Setelah investigasi mendalam sambil ngopi, inilah tiga biang kerok yang paling bertanggung jawab:
1. Ekonomi ‘Senyum Dulu, Nangis di Kosan’
Pariwisata adalah bos kita semua. Dan si bos ini nuntut kita buat selalu senyum 24/7, ramah ke bule, sambil bilang “terima kasih” padahal saldo ATM setipis tisu dibagi dua. Tuntutan buat tampil sempurna di depan turis seringkali berbanding terbalik sama kondisi dompet. Inilah wajah pertama dari tekanan hidup di Bali: kesenjangan antara fasad dan finansial.
2. Adat & Tradisi ‘Paket Komplit Plus Stres’
Kita bangga sama budaya kita, sumpah. Tapi mari akui, jadwal odalan kadang lebih padat dari jadwal tur konser K-Pop. Biaya untuk upacara, banten, dan tetek bengek lainnya kalau dihitung-hitung bisa buat DP rumah di Cikarang. Ini bukan berarti kita nggak cinta adat, tapi tekanan finansial dan sosial untuk “tidak kelihatan kere” saat upacara itu nyata adanya, cuy.
3. Lingkungan Sosial ‘Keponya Ngalahin Intel’
Konsep Menyama Braya itu indah, artinya persaudaraan. Tapi efek sampingnya? Privasi jadi barang langka. Pertanyaan “Kapan kawin?”, “Kok belum isi?”, “Kerja di mana sekarang?”, “Kapan beli Fortuner kayak tetangga sebelah?” itu udah kayak lagu wajib yang diputar setiap ada kumpul keluarga. Tekanan buat memenuhi ekspektasi sosial ini kadang lebih berat dari bawa galon air ke lantai empat.
Jadi, Solusinya Cuma ‘Healing Sambil Nangis di Pantai’?
Terus gimana? Apa kita cuma bisa pasrah, bikin story Instagram “Bali is crying” terus lanjut ngopi di coffeeshop estetik? Ya nggak gitu juga, Ferguso.
Langkah pertama adalah berhenti menganggap kesehatan mental itu aib. Ngobrolin soal depresi atau kecemasan itu harusnya sama normalnya kayak kita ngeluhin Vario yang tiba-tiba brebet. Wajar, manusiawi, dan butuh “dibengkelin”.
Coba deh, sekali-kali tanya temenmu, “Lo beneran oke, nggak?” bukan cuma “Nongkrong di mana ntar malem?”. Kadang, kepedulian kecil itu efeknya lebih manjur dari sound healing di Ubud. Jika butuh bantuan lebih, jangan ragu hubungi profesional seperti layanan konseling psikologi terdekat.
Pada akhirnya, mari kita bikin Bali jadi surga beneran. Bukan cuma surga di feed Instagram, tapi juga surga di dalam kepala para penghuninya.