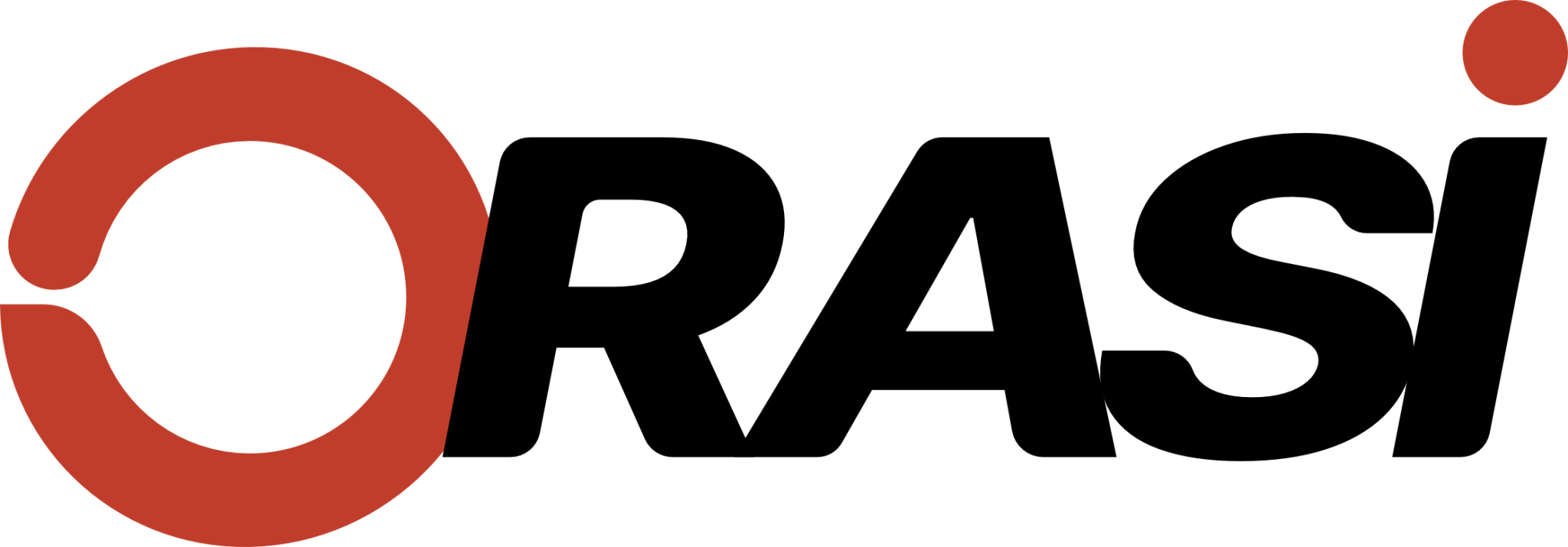Wacana baru kembali menyeruak dari Pak Koster. Katanya, bakal ada trayek baru Trans Metro Dewata yang melayani rute Singaraja – Denpasar PP via shortcut.
Iming-imingnya manis banget, Ton. Warga Buleleng yang kerja atau kuliah di Denpasar katanya nggak perlu nge-kos lagi. Cukup duduk manis di bus, pulang pergi tiap hari. Hemat biaya hidup, katanya. Sebuah mimpi indah di siang bolong, atau solusi jenius?
Sebelum kita buru-buru tepuk tangan atau siap-siap checkout dari kosan, mari kita bedah realita Trans Metro Dewata yang sudah ada di depan mata. Jangan sampai ekspansi ini cuma jadi cara baru buat memindahkan “kemacetan” dan “anggaran” tanpa solusi nyata.
Data Penumpang Trans Metro Dewata: Realita Pahit 30%
Kalau pemerintah bilang program ini sukses karena sudah mengangkut total 8,2 juta penumpang sejak 2020, jangan langsung percaya, Ton. Itu namanya vanity metric alias angka buat gaya-gayaan.
Fakta di lapangan berbicara lain. Data tahun 2024 menunjukkan load factor (tingkat keterisian) bus merah ini rata-rata cuma di angka 30%.
Artinya apa? 70% sisa kursinya itu kosong melompong. Bus segede gaban itu seringkali cuma ngangkut angin, sopir, dan mungkin satu dua penumpang yang lagi gabut. Kalau rute dalam kota (urban) yang padat kayak Denpasar – Badung – Tabanan – Gianyar (Sarbagita) saja sepi peminat, kok berani-beraninya mau buka rute antar-kota (AKDP) yang jarak tempuhnya 3-4 jam PP?
Apakah Trans Metro Dewata rute Singaraja nanti bakal bernasib sama? Jadi “Bus Hantu” versi long trip?
Kenapa Trans Metro Dewata Sepi Peminat?
Kegagalan TMD menarik minat warga Bali bukan karena kita manja atau malas. Ada masalah fundamental yang bikin orang mikir seribu kali buat ninggalin motor NMAX-nya. Berikut borok-boroknya:
1. Trust Issue: Drama “Mati Suri”
Masih ingat awal tahun 2025 kemarin? Trans Metro Dewata sempat berhenti beroperasi alias “mati suri” selama berbulan-bulan (Januari – April). Alasannya klasik: masalah lelang dan anggaran.
Bayangkan kalau khe sudah menggantungkan hidup sama bus ini buat kerja, tiba-tiba busnya ghosting. Sakit, Ton! Kepercayaan publik itu mahal. Sekali dikecewakan, warga bakal balik lagi ke motor pribadi yang lebih setia.
2. Fasilitas “Neraka” & Tidak Ramah Pejalan Kaki
Konsep Bus Rapid Transit (BRT) itu satu paket sama fasilitas pendukung. Masalahnya, halte TMD seringkali panas kayak oven. Belum lagi akses menuju halte.
Di Bali, trotoar itu barang mewah. Kalaupun ada, seringnya bolong-bolong, dipakai parkir, atau jualan canang. Mau naik bus harus jalan kaki 1 KM di trotoar rusak sambil pakai kebaya atau udeng? Sing main! Selain itu, feeder (angkot penyambung) ke perumahan juga gaib. Turun di halte, terus mau ke rumah naik apa? Teleportasi?
3. Marketing Kaku, Kalah Jauh sama Ojol
Coba bandingkan saat Gojek atau Grab pertama kali masuk Bali. Mereka gandeng influencer, artis, dan bikin kampanye masif bahwa naik ojol itu “keren” dan solutif.
Sosialisasi Trans Metro Dewata? Kaku banget kayak apel pagi PNS. Nggak ada pelibatan komunitas, nggak ada campaign kreatif yang bikin Gen Z merasa relate. Hasilnya? Bus ini cuma dianggap “proyek pemerintah”, bukan “gaya hidup”.
Solusinya: Salah Manajemen, Bukan Salah Busnya
Sebenarnya, kehadiran Trans Metro Dewata itu sudah ada di jalur yang benar (on the right track). Bali butuh transportasi massal, titik. Kita nggak bisa selamanya bergantung pada kendaraan pribadi kalau nggak mau pulau ini jadi lautan macet total.
Tapi, masalah utamanya ada di Manajemen dan Ekosistem. Barangnya benar, tapi kokinya salah racik.
Sebelum Pak Koster atau pemerintah sibuk nambah trayek jauh ke Buleleng, tolong bereskan dulu PR di Denpasar:
- Pastikan bus nggak ghosting lagi.
- Perbaiki trotoar dan akses halte.
- Sediakan feeder yang jelas sampai ke gang-gang perumahan.
- Ubah gaya komunikasi biar masuk ke otak anak muda.
Jadi, gimana menurut khe, Ton? Mending gass terus bikin trayek Singaraja, atau benahi dulu yang ada biar nggak mubazir anggaran?